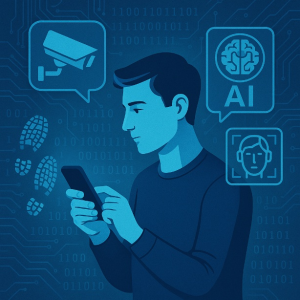Oleh: Siska Nur Azqia
Dalam lanskap ekonomi global yang semakin terhubung, urusan perpajakan bukan lagi soal kedaulatan semata. Munculnya Global Minimum Tax (GMT) kebijakan pajak internasional yang digagas oleh OECD dan G20 menandai babak baru dalam pengelolaan fiskal dunia. Di satu sisi, GMT digadang-gadang sebagai solusi untuk mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Tapi di sisi lain, ia mengusik satu pertanyaan mendasar: apakah kita masih sepenuhnya berdaulat atas pajak yang kita kenakan?
GMT menetapkan batas bawah tarif pajak efektif sebesar 15% terhadap perusahaan multinasional dengan omzet global lebih dari €750 juta. Jika suatu negara mengenakan tarif pajak di bawah ambang itu, maka negara domisili perusahaan bisa memungut kekurangannya melalui mekanisme top-up tax. Secara teori, ini mencegah persaingan tarif rendah yang menggerus penerimaan negara. Tapi bagi negara berkembang seperti Indonesia, sistem ini bisa berarti hilangnya kontrol terhadap kebijakan fiskal sendiri.
Indonesia memang telah menunjukkan kesiapan dengan menyelaraskan GMT ke dalam kerangka hukum nasional melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, kenyataannya tak sesederhana itu. Banyak insentif yang selama ini menjadi andalan pemerintah seperti tax holiday, super deduction, hingga fasilitas pajak di Kawasan Ekonomi Khusus berpotensi menjadi tak relevan. Ketika tarif efektif lebih rendah dari 15%, insentif tersebut tidak lagi menarik karena pajak tetap harus dibayar di negara asal perusahaan. Maka yang terjadi bukan hanya kehilangan fleksibilitas fiskal, tapi juga hilangnya sebagian hak memajaki yang selama ini kita miliki.
Di sinilah kegalauan muncul. Global Minimum Tax memang didesain untuk menciptakan keadilan pajak lintas negara. Tapi jika arsitekturnya dirancang oleh negara-negara maju yang menjadi rumah bagi raksasa-raksasa multinasional, maka siapa sebenarnya yang akan paling diuntungkan? Negara berkembang seperti Indonesia bisa saja hanya menjadi “ladang aktivitas ekonomi” yang tak sepenuhnya bisa memetik hasil perpajakannya sendiri. Kedaulatan fiskal yang selama ini kita anggap absolut, bisa perlahan-lahan tergeser oleh norma global yang semakin mengikat.
Tentu, bukan berarti Indonesia harus menarik diri dari arus global. Tapi perlu langkah cerdas untuk memastikan bahwa pajak tetap menjadi alat pembangunan nasional, bukan semata instrumen yang dikendalikan dari luar. Pemerintah perlu merancang strategi baru mengalihkan insentif ke bentuk non-pajak, memperkuat posisi tawar dalam forum internasional, dan memperjuangkan keadilan distribusi pendapatan pajak dalam kerangka GMT.
Karena pada akhirnya, pajak bukan hanya soal angka. Ia adalah tentang pilihan politik, prioritas pembangunan, dan hak suatu bangsa untuk menentukan arah ekonominya sendiri. Dan ketika sebagian dari hak itu mulai tergantung pada regulasi global, wajar kalau kita bertanya: masihkah pajak itu sepenuhnya milik kita?