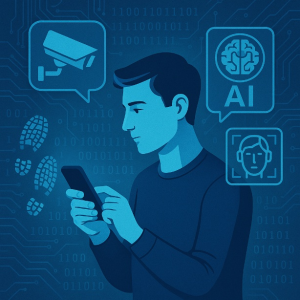Penulis : Athala Radja Diksana,
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (KemenkopUKM, 2023). Peran penting ini menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam agenda pembangunan nasional, termasuk dalam aspek perpajakan. Namun, pertanyaannya: apakah kebijakan pajak yang berlaku saat ini benar-benar adil dan berpihak pada pelaku UMKM?
Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021), pemerintah merancang sejumlah reformasi perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi dan memperluas basis pajak, termasuk untuk sektor UMKM. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet bruto, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Skema ini memberikan kemudahan administratif, karena pelaku UMKM tidak diwajibkan membuat pembukuan secara rinci—cukup dengan pencatatan omzet. Selain itu, pelaku usaha dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta dibebaskan dari kewajiban membayar PPh. Secara sepintas, kebijakan ini tampak ramah terhadap UMKM dan memberikan angin segar bagi pelaku usaha kecil.
Namun, keadilan pajak semestinya tidak hanya diukur dari rendahnya tarif atau keringanan administratif. Aspek kemampuan membayar, akses informasi, dan pendampingan juga harus menjadi indikator utama. Di lapangan, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki literasi perpajakan yang memadai, apalagi akses terhadap konsultan pajak atau sistem pelaporan elektronik. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang terlambat melaporkan pajak atau terkena sanksi administratif akibat kekeliruan prosedural. Survei Katadata Insight Center tahun 2023 mengungkap bahwa lebih dari 60% UMKM tidak memahami kewajiban perpajakan mereka secara menyeluruh, sebuah angka yang menunjukkan jurang besar antara regulasi dan kapasitas pelaku usaha.
Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat ada ketimpangan antara semangat regulasi dengan kenyataan di lapangan. Dalam teori hukum pajak, dikenal asas ability to pay atau asas kemampuan membayar sebagai prinsip dasar keadilan. Artinya, kewajiban pajak seharusnya menyesuaikan kondisi riil pelaku usaha. Dalam praktiknya, ketika omzet UMKM menurun akibat tekanan ekonomi atau krisis, pungutan pajak yang tetap didasarkan pada omzet bruto tanpa mempertimbangkan margin keuntungan bisa menjadi beban berat. Di sisi lain, sistem self-assessment yang berlaku juga belum diimbangi dengan pendampingan atau sosialisasi yang merata, terutama di wilayah luar Jawa yang akses teknologinya masih terbatas.
Dalam perspektif hukum tata negara, Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan fiskal. Meskipun UU HPP telah membuka ruang fleksibilitas melalui penyesuaian tarif dan pembebasan kewajiban pajak bagi golongan tertentu, pelaksanaannya masih terkendala pada sisi literasi dan keterjangkauan. Bahkan, hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), padahal itu adalah elemen dasar dalam sistem perpajakan nasional.
Fakta menarik lainnya adalah bahwa menurut laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2022, kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif, penerimaan pajak dari sektor ini bisa ditingkatkan tanpa harus menerapkan pendekatan koersif atau represif. Salah satu langkah strategis yang bisa diambil adalah memperluas program inklusi perpajakan ke dalam pendidikan dasar dan menengah, atau menyelenggarakan pelatihan langsung di komunitas pelaku usaha.
Keadilan fiskal juga harus dibaca dalam konteks persaingan usaha yang sehat. UMKM kerap kali berada pada posisi yang tidak setara saat berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki struktur dan perencanaan pajak yang jauh lebih kompleks. Bahkan, tidak sedikit perusahaan besar yang memanfaatkan celah hukum untuk melakukan praktik tax avoidance secara legal namun tidak etis. Di tengah kondisi tersebut, pelaku UMKM yang patuh justru bisa merasa tidak diuntungkan, karena mereka membayar pajak sesuai aturan, sementara entitas besar punya ruang untuk “mengatur” kewajiban fiskalnya. Ini jelas mencederai prinsip keadilan fiskal dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.
Sebagai penutup, saya meyakini bahwa keadilan pajak bagi UMKM bukan hanya persoalan tarif rendah, tetapi soal bagaimana sistem perpajakan dibangun untuk berpihak, mendampingi, dan memberdayakan. Negara tidak cukup hanya berperan sebagai pemungut pajak, tetapi harus hadir sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Dengan kebijakan yang responsif, edukasi yang berkelanjutan, serta reformasi administratif yang inklusif, saya percaya cita-cita pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud tanpa mengorbankan rasa keadilan dalam sistem perpajakan nasional.