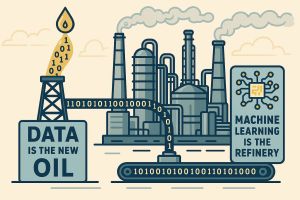Oleh: Fahmi Muhammad Fakhruddin
NIM: 241011500144
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pamulang (UNPAM)
Reguler: CS
Kelas: 03PPKE001
Tugas Mata Kuliah: Hak Asasi Manusia
Dosen Pengampu: Bpk. Dr. Herdi Wisman Jaya S.Pd., M.H.
HAM sebagai Kewajiban Konstitusional
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kewajiban dasar yang secara khusus diamanatkan oleh konstitusi di Indonesia. Landasan utama instrumen HAM nasional terletak pada Bab XA UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (diperkenalkan melalui Amandemen Kedua), yang memberikan payung hukum bagi setiap warga negara. Instrumen domestik ini unik, sebab ia dirancang untuk menginternalisasi standar HAM universal sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Pancasila (Asshiddiqie, 2012).
Karakteristik 1: Kekuatan Mengikat dan Supremasi Kedaulatan Hukum
Kekuatan instrumen nasional terletak pada statusnya sebagai hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara mutlak di seluruh wilayah kedaulatan negara. Ratifikasi instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), harus ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Domestik (misalnya, UU No. 12 Tahun 2005) agar dapat diimplementasikan sepenuhnya (Jimly, 2005).
Kedaulatan hukum ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan. Pembentukan Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000) menunjukkan komitmen negara untuk mengadili sendiri Pelanggaran HAM Berat. Menurut Komnas HAM (2020), adanya pengadilan khusus ini mencerminkan prinsip yurisdiksi teritorial Indonesia dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Karakteristik 2: Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Bingkai Pancasila
Ciri khas instrumen HAM nasional Indonesia adalah penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 secara tegas menetapkan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Konsep ini berbeda dengan fokus utama beberapa instrumen internasional yang cenderung menekankan kebebasan individual. Dalam konteks Indonesia, pembatasan HAM (seperti diatur dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 70 UU No. 39/1999) didasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Marbun (2000) yang melihat bahwa HAM dalam konteks Indonesia harus selalu didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mencegah penggunaan hak secara absolut yang merugikan kepentingan sosial.
Karakteristik 3: Kelembagaan dan Spesialisasi Perlindungan
Karakteristik penting instrumen nasional adalah penciptaan kerangka kelembagaan yang independen dan spesialis. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan UU No. 39/1999 dan diperkuat oleh Tap MPR No. XVII/MPR/1998 menjadikannya lembaga quasijudisial yang bertugas mengkaji, memantau, dan melakukan penyelidikan (HRW, 2021).
Selain itu, instrumen nasional juga berfokus pada kelompok rentan dengan mendirikan lembaga spesialis seperti Komnas Perempuan dan KPAI, serta mengundangkan peraturan khusus, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Spesialisasi ini penting untuk mengatasi diskriminasi struktural yang membutuhkan perangkat hukum yang lebih detail dan afirmatif.
Penutup: Tantangan Implementasi dan Harapan
Meskipun fondasi hukum dan karakteristiknya unik, tantangan utama instrumen HAM nasional terletak pada efektivitas implementasi. Laporan Komnas HAM sering kali tidak diiringi dengan tindak lanjut yang memadai dari lembaga penegak hukum (KontraS, 2023). Oleh karena itu, penguatan HAM domestik di masa depan tidak hanya membutuhkan kesempurnaan regulasi, tetapi juga transformasi budaya ketatanegaraan dan komitmen politik yang sungguh-sungguh. Karakteristik instrumen nasional harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa perlindungan HAM di Indonesia berjalan seimbang, berdaulat, dan sesuai dengan cita-cita Pancasila.
Referensi:
• Asshiddiqie, Jimly. (2012). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
• Human Rights Watch (HRW). (2021). World Report 2021: Indonesia.
• Jimly, Asshiddiqie. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
• Komnas HAM. (2020). Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020. Jakarta: Komnas HAM.
• KontraS. (2023). Catatan Akhir Tahun 2023: Pelanggaran HAM di Indonesia.
• Marbun, B. N. (2000). Dimensi-Dimensi HAM dalam Konstitusi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).