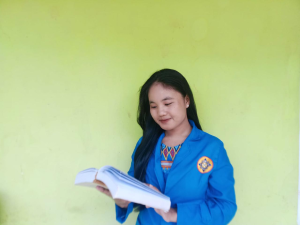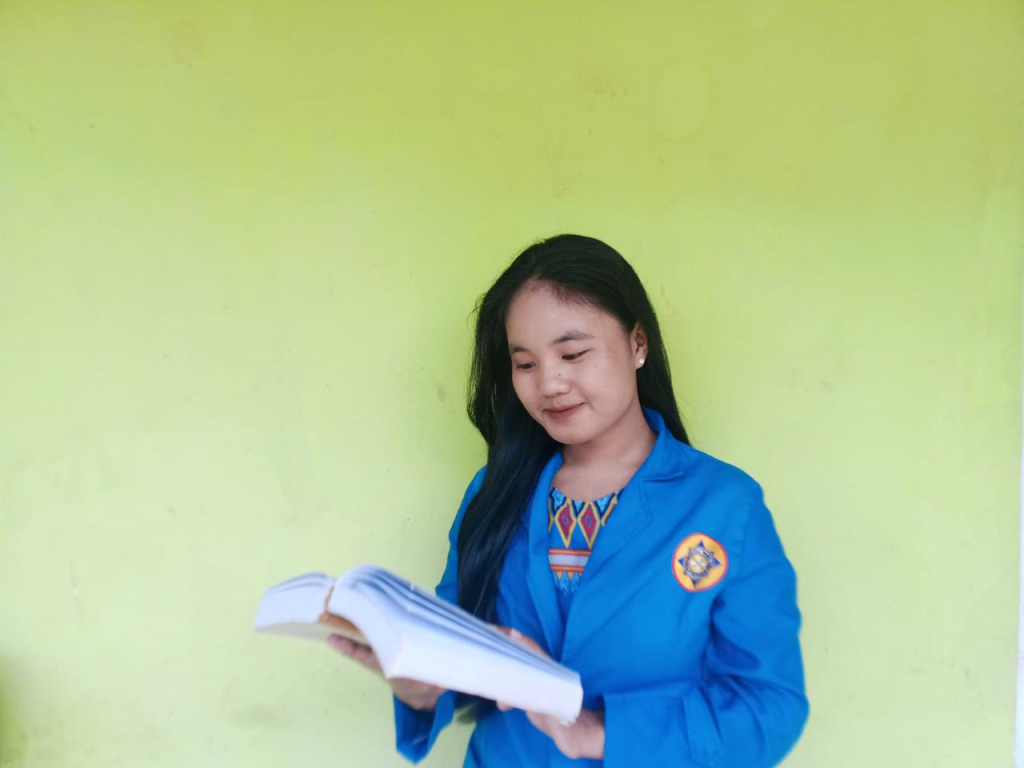
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang mengusung prinsip politik luar negeri “Bebas dan Aktif” dengan semangat Non-Bloc, yakni tidak memilih salah satu pihak dalam persaingan kekuatan global. Prinsip ini menjadi landasan dalam menjaga kedaulatan serta independensi dalam menentukan kebijakan internasional. Namun, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS kelompok negara dengan agenda politik dan ekonomi yang tidak netral menimbulkan perdebatan terkait konsistensi dan implementasi prinsip tersebut. Kritik mucul bahwa langkah ini bertentangan dengan semangat Non-Bloc yang telah menjadi identitas diplomasi Indonesia sejak konferensi Asia-Afrika 1955.
Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS menghadirkan dinamika yang kontradiktif terhadap prinsip Bebas dan Aktif serta semangat Non-Bloc yang selama ini dijunjung tinggi. Kelompok BRICS merupakan sebuah aliansi strategis yang dibentuk untuk menyeimbangkan pengaruh kekuatan Barat, didominasi oleh negara-negara besar seperti Tiongkok dan Rusia yang memiliki tujuan politik dan ekonomi yang sangat terarah. Dalam konteks ini, keanggotaan Indonesia pada BRICS bukanlah bagian dari sikap netral, melainkan penempatan diri dalam sebuah blok yang jelas memiliki agenda geopolitik.
Sejak era Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak terjebak dalam bipolaritas Perang Dingin, menolak berperang di pihak manapun. Namun, keikutsertaan dalam BRICS dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran terhadap posisi netral itu. Dengan demikian, klaim bahwa keanggotaan BRICS sesuai dengan prinsi Bebas dan Aktif kurang memiliki dasar argumentasi yang kuat. Prinsip tersebut seharusnya melekat pada sikap tidak memihak dan menjaga independensi dalam hubungan internasional. Penempatan Indonesia berdampingan dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia menimbulkan keraguan terhadap citra negara yang selama ini dipandang netral oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang.
Pemerintah beralasan bahwa keanggotaan di BRICS memberikan keuntungan ekonomi, seperti akses kefasilitas bank pembangunan dan jalur perdagangan alternatif. Namun, risiko ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik yang mendominasi BRICS, khususnya Tiongkok dan Rusia, menjadi persoalan strategis. Indonesia, sebagai negara penyedia sumber daya alam, berpotensi berada pada posisi tawar yang lemah. Ketergantungan ini berisiko mengurangi kemampuan diplomasi Indonesia dalam mengangkat isu-isu kedaulatan seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan.
Pertanyaan penting yang perlu dianalisis adalah :
- Apakah Indonesia mampu menjaga kebebasan dalam mengeluarkan suara terkait isu-isu sensitif tanpa terjerat dalam tekanan politik dari anggota BRICS yang memiliki kepentingan kuat?
- Bagaimana kesiapan Indonesia dalam menggunakan mata uang selain dolar AS, khususnya Yuan Tiongkok, yang jika tidak diatur dengan cermat dapat meningkatkan kerentanan finansial dan politis terhadap Tiongkok?
Untuk merealisasikan politik luar negeri yang benar-benar mandiri di tengah dinamika global, Indonesia sebaiknya memperkuat kerangka Non-Bloc yang asli atau mengoptimalkan perannya dalam ASEAN, daripada memasuki blok geopolitik dengan agenda kuat. Bergabung dengan BRICS dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa posisi Indonesia dalam politik Non-Bloc melemah atau negara merasa belum cukup kuat berdiri sendiri sehingga membutuhkan perlindungan kelompok lain.
Walaupun keanggotaan BRICS memberikan potensi keuntungan ekonomi jangka pendek, biaya jangka panjangnya adalah berkurangnya integritas politik dan posisi tawar Indonesia di pentas internasional. Non-Bloc bukan sekadar label kosong yang dapat dikorbankan demi keuntungan pragmatis. Indonesia
perlu melakukan evaluasi strategis agar prinsip Bebas dan Aktif tetap menjadi fondasi kebijakan luar negeri yang kokoh dan relevan di era globalisasi dan multipolaritas saat ini.